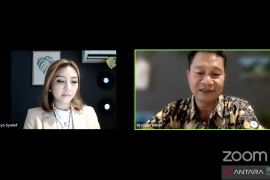Jakarta (ANTARA) - Pakar politik Saiful Mujani memperlihatkan kepada publik tentang raibnya suara hati politisi senior Amien Rais yang bilang bahwa people power itu enteng-entengan.
Amien Rais, yang punya latar belakang bergengsi sebagai ilmuwan politik dengan disiplin hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada, yang pada dasawarsa 80-an komentar-komentarnya tentang percaturan politik kawasan Timur Tengah banyak dikutip media massa terkemuka, juga seorang kolumnis berwibawa saat itu.
Ialah yang membangkitkan kembali frasa people power ke dalam konteks politik mutakhir, dengan kalimat-kalimat yang intimidatif sekaligus bermuatan unsur penghinaan terhadap lembaga hukum.
Terlepas dari kontroversi apakah tragedi 22 Mei lalu yang berlangsung di Jalan KS Tubun Petamburan dan Jalan Thamrin, Jakarta, itu bisa dikategorikan sebagai gerakan kekuatan rakyat atau bukan, fenomena yang muncul adalah jatuhya korban tewas, korban luka-luka, dan kerugian material.
Untuk standar demokrasi yang ideal, tragedi 22 Mei itu jelas perkara besar, tidak enteng-entengan sebagaimana dilontarkan Saiful yang murid indonesianis William Liddle dari Univeristas Ohio, AS itu.
Maka pokok perkara demokrasi yang sedang berlangsung di Tanah Air adalah bagaimana meminimalkan kekerasan, apalagi yang sampai menelan korban nyawa, baik dari kalangan warga negara biasa ataupun aparat penegak hukum.
Artinya, pakem-pakem berdemokrasi yang dipertontonkan kaum demokrat sejati dalam rentang sejarah politik global gagal dipraktikkan oleh elite politik yang bertanding dalam laga Pemilihan Presiden 2019.
Demokrasi dengan seminim mungkin kekerasan memang tak bisa dibangun secara sepihak tapi harus diperjuangan bersama-sama, baik oleh para elite politik yang berkompetisi maupun para simpatisan para elite yang bersaing itu.
Andaikan Amien Rais tak mencetuskan ide atau narasi people power , tak ada alasan bagi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersuara tentang perlunya tentara mengamankan keabsahan pemerintahan dan kedaulatan negara.
Maraknya kekerasan dalam perpolitikan suatu negara mengindikasikan belum mantapnya mekanisme penyelesaian perkara secara politis, oleh elite politik sesuai dengan aturan main yang beradab.
Isu yang berkembang yang mengikuti isu sentral Pilpres 2019 tak berfokus pada kesiapan kandidat yang kalah untuk mengucapkan selamat kepada sang pemenang, namun melebar ke perkara pidana seperti penyelundupan senjata, adanya penyandang dana di balik aksi kekerasan 22 Mei.
Tampaknya, pekerjaan rumah yang cukup berat dalam memantapkan demokrasi di Tanah Air adalah mendidik sejak dini generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan untuk berjiwa kesatria ketika harus menelan kekalahan dalam berkompetisi di ranah politik.
Refleksi itu antara lain bisa dalam mentuk mencari jawaban atas pertanyaan klasik ini: kenapa syahwat politik begitu kuat hingga menyingkirkan hasrat mengalah? Kenapa ada kecenderungan di kalangan elite politik untuk memaknai keagungan hanya pada takhta di kursi kekuasaan? Kenapa kesabaran untuk menang yang terkemas dalam bentuk keyakinan akan masa depan yang penuh pengharapan telah raib?
Tampaknya refleksi semacam itu cukup krusial setidaknya untuk menghindari tragedi yang belangsung 22 Mei lalu, yang pada tataran verbal tercermin pada kontradiksi Amien Rais versus Saiful Mujani.
Baca juga: Amien Rais perlu dipanggil terkait rencana pembunuhan pejabat negara
Copyright © ANTARA 2019