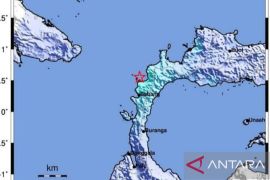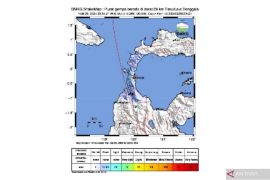Guncangan yang menghempas dan merobohkan rumah, air bah setinggi pohon kelapa yang mengejar dan menerkam, hingga bumi yang menelan semua bangunan di atasnya menyisakan trauma tersendiri bagi yang menyaksikannya.
Gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018) menjelang malam itu begitu mencekam, membuat sekitar 67 ribu rumah rusak, menewaskan lebih dari 2.000 jiwa, 600-an lainnya masih hilang, lebih dari 10 ribu orang luka dan patah tulang serta menyebabkan hampir 83 ribu jiwa mengungsi.
Tidak sedikit anak-anak yang terguncang karena menyaksikan sendiri peristiwa kelam tersebut, rumah-rumah bergerak, retak-retak dan roboh mengubur banyak kenangan masa kecil sambil menyaksikan orang-orang dewasa yang berlarian panik.
Seminggu setelah peristiwa, Posko Kemensos sempat mencatat sedikitnya ada delapan anak yang terpisah dari keluarganya.
Juru Bicara Command Center Kementerian Sosial untuk bencana Sulawesi Tengah Adhy Karyono mengatakan, dari anak-anak yang terpisah itu sudah ada beberapa yang bertemu orang tuanya, sebagian yang lain dikumpulkan di "shelter" dan sedang ditelusuri keluarganya.
Jika tidak juga ditemukan keluarganya atau memang sudah dinyatakan menjadi korban meninggal dunia saat terjadi bencana, maka si anak akan diurus negara di panti-panti asuhan. Namun demikian, negara membuka opsi adopsi untuk memberi peluang bagi si anak memperoleh keluarga.
Anak yang kehilangan orang tua dan kerabatnya tersebut, diakuinya, sangat rentan menjadi korban perdagangan anak atau eksploatasi anak, dan karena itu opsi adopsi memiliki aturan yang ketat dan prosedur yang tidak sederhana.
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi mengatakan, anak-anak yang baru saja tertimpa musibah memang perlu segera mendapat penanganan dan pemulihan trauma pascabencana.
Tujuannya agar mereka bisa segera melupakan kesedihannya, bisa kembali bergembira, dan merasakan kondisi di sekitarnya tampak normal seperti biasa.
Merintih terisak-isak dan menangis sambil memanggil nama orang tuanya merupakan reaksi yang biasa diperlihatkan oleh anak-anak yang bingung, ketakutan dan merasa kehilangan.
Bukan saja karena peristiwa mencekam yang disaksikan si anak, tetapi juga suasana pengungsian yang berjejalan dan penuh orang tidak dikenal, ditambah lagi kehilangan orang-orang terdekat.
Anak-anak, menurut dia, memang merupakan kelompok masyarakat yang paling mudah terkena trauma saat terjadi bencana semacam ini dibandingkan orang yang lebih dewasa, namun demikian mereka juga paling cepat untuk kembali pulih bila ditangani secara tepat.
Selain itu, gejala traumatis pada anak bisa lebih cepat hilang jika keluarga serta komunitas setempat memberi dukungan dalam pemulihan tersebut, sebaliknya anak-anak yang tidak mendapat dukungan pemulihan dari orang-orang terdekatnya seringkali mengalami gejala traumatis yang lebih lama dan berlanjut lebih dari sebulan.
Menurut dia, anak dengan pengalaman trauma saat bencana yang mengguncang jiwanya akan berdampak buruk pada kepribadian si anak kelak.
Kepribadian itu misalnya, kurang percaya diri, cepat marah dan mudah meledak-ledak, tidak bisa bekerja sama, tidak percaya pada orang lain, waspada secara berlebihan, menarik diri dari lingkungan. Ditambah lagi potensi-potensi yang sebenarnya ada pada dirinya pun ikut meredup.
Penuh ketidakpastian
Anak-anak yang menjadi korban bencana dan harus tinggal dalam pengungsian mengalami banyak perubahan pada rutinitas hidup dan lingkaran sosial mereka yang biasa menjadi penuh ketidakpastian.
Jika biasanya setiap pagi si anak mendapat sarapan dari si ibu lalu pergi ke sekolah, maka di tempat pengungsian, mungkin ia harus menahan lapar, tidak bersekolah dan juga kehilangan teman-teman bermainnya.
Demikian pula begitu matahari sore telah menghilang, si anak hanya bisa menjejalkan diri di antara orang-orang dewasa yang cemas dan kurang dikenalnya, di bawah terpal beralas tikar dan lagi-lagi juga menahan lapar.
Trauma pada anak lima tahun ke bawah, menurut National Institute of Mental Health Amerika Serikat (AS), biasanya ditampakkan dengan tanda-tanda ketakutan, menangis, menjerit, melekat terus dengan orang terdekatnya, menjadi pendiam, atau sebaliknya bergerak terus tanpa tujuan atau kembali mengompol dan mengisap jempol.
Sedangkan untuk anak-anak di atas lima tahun ditampakkan dengan mimpi buruk, sulit tidur, perasaan hampa, kehilangan minat terhadap lingkungan sosialnya, sedih, cemas, ketakutan, mudah tersinggung, sering marah-marah, suka mengeluh, bahkan menjadi pengganggu.
Sejumlah terapi pemulihan untuk anak-anak yang terkena trauma pascabencana telah lama diusulkan oleh para psikolog. Tujuannya membuat anak menjadi lebih mampu untuk hidup di masa kini dan masa depan tanpa dibebani oleh pikiran dan perasaan masa lalu.
Pakar psikologi AS Jeanne Segal PhD, misalnya, melihat pentingnya anak dijauhkan dari pemberitaan mengenai bencana yang terus mengingatkannya akan peristiwa menakutkan tersebut.
Karena itu menonton film kartun atau siaran komedi anak lebih dianjurkan daripada menonton berita yang menampilkan gambar-gambar mencekam.
Segal juga melihat pentingnya menjaga rasa nyaman si anak dengan melakukan hal-hal yang normal seperti yang selama ini dia lakukan sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa traumatisnya.
Mengajak anak bermain seperti tebak-tebakan dengan kartu, bermain dadu, atau menikmati apa yang menjadi hobi dan kesenangannya seperti mewarnai, atau melakukan hal-hal lain yang membuat mereka tertawa gembira, sangat dianjurkan.
Mengajak anak berpartisipasi dalam aktivitas fisik seperti berolahraga senam atau balapan lari, bermain petak umpet atau semacamnya serta menari dan menyanyi dapat membantu membangunkan sistem saraf anak-anak terdampak trauma dari perasaan terjebak yang sering kali mengikuti pengalaman traumatis.
Selain itu, anak-anak ini perlu diajak melihat cerahnya masa depan dengan optimisme serta diajak membuat rencana kegiatan hari esok untuk menangkal pandangannya bahwa masa depannya suram, dan menakutkan.
Mereka perlu dibantu dengan membuat dunia menjadi tampak stabil dan cerah. Sebab kejadian traumatis memang dapat mengubah cara seorang anak melihat dunia menjadi lebih kelam dan gelap.
Karena itulah optimisme sangat penting dibangun dalam pemulihan pascabencana. Optimisme juga dinilai bisa membuat anak mampu menerima keadaan dan membuatnya tergerak untuk lebih bersemangat melihat hari esok.
Baca juga: Mulai banyak layanan psikososial di pengungsian Palu
Pewarta: Dewanti Lestari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2018