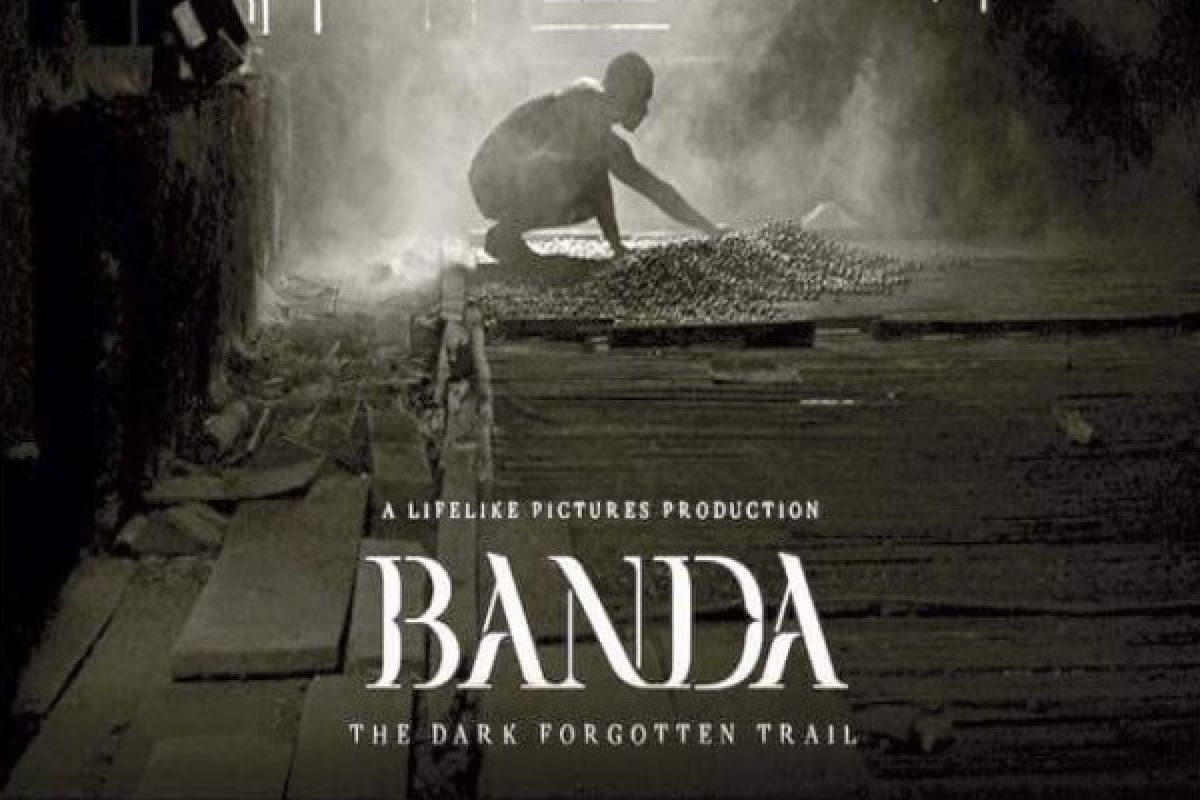... membuat film dokumenter sejarah murni menjadi dua tiga kali lipat lebih susah dari film biasa ...Judul: Banda The Dark Forgotten Trail
Sutradara: Jay Subyanto
Sinematografi: Ipung Rachmat Syaiful
Naskah: Irfan Ramli
Produksi: Lifelike.
Jakarta (ANTARA News) - Film karya pertama Jay Subyakto "Banda the Dark Forgotten Trail" (BTDFT), satu film dokumenter panjang sejarah murni, mulai ditayangkan 3 Agustus 2017.
Di luar upaya sangat serius untuk merekonstruksikan salah satu keping sejarah bangsa Indonesia yang perlu sangat kita apresiasi, dan hampir seluruh aspek filmis di film ini yang ditampilkan secara baik, kita perlu mencatat justru pada aspek keotentikan dan argumentasi kesejarahan film ini masih menimbulkan sejumlah tanda tanya, kalau tidak mau disebut sebagai titik lemah.
Contoh, ketika narasi film berujar, bangsa Arab sampai berbohong soal Pulau Banda karena urusan pala, tak ada rujukan atau keterangan, apalagi argumentasi yang terang benderang. Darimana kita tahu mereka berbohong dan kenapa mereka harus berbohong? Lantas siapa yang dibohongi?
Dengan begitu, kalimat dalam narasi seakan hanya untuk memberikan efek aksentuasi "bombastis." Berlainan kalau ada, cukup dua atau tiga kalimat berupa data penunjang argumentasi, sehingga penonton dapat diyakini.
Menarik pula untuk menggali lebih dalam, kenapa pada perjanjian tahun 1667 antara Inggris dan Belanda, pihak Belanda sampai berani melakukan pertukaran wilayah Nieuw Amsterdam (sekarang dikenal Manhattan, New York). Sebagai penonton film sejarah murni, kita tentu ingin tahu bagaimana secara umum perhitungannya? Siapa dapat apa, dan mengapa?
Data seperti ini akan memperkuat struktur kesejarahan kehebatan pala Palau Banda. Tak hanya cukup dengan dalil waktu itu, "segenggam pala lebih bernilai daripada segenggam emas".
Namun, bagaimana hitungannya sehingga Belanda nekad menyerahkan Manhattan yang jelas punya prospek sangat bagus kepada Inggris? Apakah dalam perspektif sejarah kini hal tersebut merupakan blunder pihak Belanda? Lalu, dari landasan sejarah masa lalu, apa pertimbangan untung rugi Belanda?
Dalam film BTDFT hal ini tidak terjawab tuntas ataupun terang. Padahal, sebagai film sejarah, hal ini sangat penting bagi penonton, serta dapat menambah bobot sejarah pentingnya pulau Banda. Kalau saja ada dua tiga kalimat dengan data penjelas, bakal menjadi penambah bobot film yang telak.
Misalnya, bagaimana dulu pohon-pohon pala itu ditanam di Pulau Banda. Insert gambar-gambar pohon pala pada zaman dulu, lengkap dengan bagaimana mekanisme pala diubah menjadi kosmetik, tumbuhan yang mengandung aprodiak dan seterusnya, pastilah menarik penonton.
(Baca juga: Banda The Dark Forgotten Trail, kisah Kepulauan Banda, pala dan Jalur Sutera)
Bagaimana Cara Belanda Membantai?
Dalam film BTDFT disebut Belanda membantai sebagin besar penduduk Pulau Banda, dan hanya menyisakan 480 orang saja. Dalam hal ini juga sebagai penonton film sejarah, kita ingin mengetahui, bagaimana cara Belanda kala itu membantai penduduk Banda sehingga hanya tinggal 480 orang saja? Apakah semua ditarik dengan empat ekor kuda dari arah yang berlainan sebagaimana diperlakukan kepada pemimpin mereka saat itu? Atau ditembak, atau digorok?
Tentu tak usah divisualkan secara harafiah, lantaran hal itu bakal menimbulkan sadisme. Namun, untuk memperkuat rekonstruksi kesejarahan itu sendiri, cara membantai penduduk Banda menjadi penting. Kejelasan ini akan menegaskan pembantaian itu bukan setengah fiktif, tapi memang benar adanya. Beberapa kalimat penjelas atau sedikit data atau argumentasi yang disodorkan, mungkin cukuplah. Namun, hal itu tidak dilakukan film BTDFT.
Kita juga ingin mengetahui, kenapa atau alasan apa, sebenarnya Belanda membuang para tokoh nasional yang waktu itu dinilai subversif ke Pulau Banda. Apakah semata-mata karena jarak Banda jauh dari Batavia? Tapi, bukankah kalau dengan alasan itu saja, Banda kala itu kaya dengan pala sehingga justru dapat memberi informasi tentang kekayaan pala di Banda ini kepada orang-orang buangan yang kelak menjadi aktor-aktor kemerdekaan Indonesia.
Itu artinya Belanda membuka celah kekayaan pala dapat diketahui. Bukankah hal ini malah riskan untuk Belanda karena dapat mendorong lebih cepatnya rasa nasionalisme?
Selain itu, bukankah masih ada juga daerah-daerah yang jauh dari pusat Batavia, seperti Boven Digul dan yang sejenisnya. Alasan utama ini belum terkuat secara menyakinkan.
(Baca juga: Film dokumenter sejarah rempah Nusantara akan tayang di Amsterdam)
Kurang Riset Internasional
Dari beberapa narasumber, khusus untuk sejarah masa lalu Banda pada film BTDFT mengandalkan sejarahwan Usman Thalib. Tentu kita memahami Usman Thalib merupakan sejarahwan andal dan punya kredibilitas baik. Tapi, untuk menghasilkan satu film sejarah murni dengan tingkat presisi yang kuat, tidak dapat cuma mengandalkan satu sumber sejarahwan saja untuk Banda masa lalu.
Selain sang narasumber sejarahwan itu, sebetulnya masih perlu pembanding buat memperkuat argumen-argumen dari film. Narasumber ahli Banda zaman dulu dari Belanda dapat menjawab kebutuhan ini. Juga data dari perpustakaan atau museum di Belanda dapat memperkuat rujukan kesejarahan Banda.
Selain itu tidak kalah pentingnya perlu riset yang mendalam, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga riset keluar negeri. Sastrawan Remy Sylado saja ketika mau menggarap novel tentang perempuan mata-mata kelahiran Indonesia, Matahari, sampai menjelajah museum-museum di Belanda untuk mencari data pendukung kesejarahan.
Memang dari riset internasional semacam itu dapat diperoleh berbagai macam data pendukung pernyataan atau kesimpulan. Sepanjang yang dipaparkan dalam film BTDFT, data tersebut tidak terungkap. Mungkin lantaran itulah banyak pernyataan dalam film ini tidak cukup didukung argumentasi berdasarkan fakta yang valid.
Walhasil, memang sebagian sisi Pulau Banda sudah mulai terkuak, tetapi pada pada sebagian besar sisi lainnya masih gelap buat kita.
(Baca juga: Warga tuntut pemutaran film Banda dibatalkan, Jay Subyakto diprotes)
Perlu Editor Andal
Pada beberapa bagian struktur BTDFT ada yang agak mengganggu irama film. Misalnya, penempatan puisi pada bagian belakangan, agak mengganggu proses penguatan pesan. Mungkin akan lebih bijak dan "kuat" kalau puisi itu ditempat pada bagian yang sedang menunjukan betapa pentingnya Pulau Banda buat Indonesia.
Hal ini karena lewat puisi tersebut memang dapat mempertajam betapa pentingnya Pulau Banda. Tetapi, dengan peletakan yang tidak tepat, maka puisi itu justru membuat film seperti anti-klimaks.
Begitu juga babak terakhir film soal bagaimana masa depan Banda yang menampilkan pendapat-pendapat khalayak umum menjadi seperti memaksakan persoalan kepada urusan ke masa depan, bukan kesejarahnya.
Soalnya, pendapat yang dirangkum umumnya tidak mengkaitkannya dengan latar belakang sejarah Banda. Walhasil, pada bagian ini malah seperti reportase televisi yang ringan saja.
Untuk film dokumentasi sejarah murni memerlukan kerja seorang editor yang andal. Seorang yang menguasai ilmu teknis editing film, tetapi sekaligus juga memperoleh data dan argumentasi dari rangkaian peristiwa sejarahnya sendiri. Dengan demikian, editor dapat menampikan kombinasi antara "dramaturgi" film dan kejelasan data sejarah.
Editor film sangat berperan menyelaraskan gambar dengan argumentasi narasi. Dengan begitu antara gambar dan narasi menyatu, bukan seperti banyak dalam berita televisi kita yang antara gambar dan suara sering tidak menyatu dan berdiri sendiri-sendiri, sehingga dengan hanya mendengar suaranya tanpa melihat gambar saja kita paham berita itu.
Film dokumenter sejarah murni memerlukan pengetahuan sejarah yang lebih detil dan kaya. Film dokumenter sejarah murni tidak hanya mememerlukan gambar-gambar indah, tetapi juga perlu dukungan banyak data yang komprehensif.
Oleh karena itu, memang membuat film dokumenter sejarah murni menjadi dua tiga kali lipat lebih susah dari film biasa, termasuk dari film dokudrama biasa.
Film sejarah murni mengekspresikan sejarah masa lalu dalam bentuk perwujudan peralatan modern. Salah satu aspek saja timpang, maka bakal memberikan efek besar dari karya film secara keseluruhan.
Editor yang dibutuhkan bukan hanya dapat memahami dan mampu melakukan aspek teknis editing film, tapi juga memiliki pemahaman terhadap data dan nilai-nilai sejarah yang sedang dibahas dalam film.
(Baca juga: Racikan dokumenter Jay Subiyakto)
Kenapa Bahasa Asing?
Hal lain yang mengusik, kenapa judul film harus memakai bahasa asing? Padahal, begitu banyak persediaan kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang tidak kalah menariknya.
Pemakaian judul bahasa asing dalam film BTDFT bukanlah perkara kecil. Kalau film komersial memakai judul bahasa asing, barangkali kita dapat "memaklumi", karena film komersial ingin dapat mengejar pasar yang lebih luas.
Film-film komersial tidak ada beban berat, selain bagaimana secara komersial dapat menggaet banyak mungkin penonton (dan sponsor).
Tapi, buat film BTDFT sebagai film yang antara lain dimaksud untuk meningkatkan rasa nasionalisme Indonesia, tentu pemakaian judul dengan bahasa asing menjadi berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai film, bahkan bertentangan.
Bukankah kalau film itu mau diikutkan berbagai festival internasional tetap dapat dipakai judul bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa asing? Pemakaian judul dalam bahasa asing membuat kontradiksi. Di satu sisi film ingin menanamkan nilai-nilai nasionalisme, tetapi di sisi lain justru mencampakkan bahasa nasional.
Bagaimana kita mau mengajar anak-anak didik yang menonton film ini untuk memiliki kebanggaan terhadap Indonesia, kalau filmnya sendiri tidak menghargai bahasa Indonesia?
(Baca juga: Reza Rahadian ngebet gabung dalam film Jay Subyakto)
Film Asli Sejarah
Film BTDFT termasuk kategori film sejarah murni. Artinya, film ini menguak, membedah dan mengedepankan persoalan sejarah Pulau Banda dalam relevansinya dengan kebangsaaan Indonesia. Secara umum kategori film sejarah murni harus menenuhi setidak-tidaknya beberapa syarat.
Pertama dan yang utama, tingkat akurasi harus tinggi, ditunjang data kuat dan lengkap. Inilah bagian tersulit film sejarah murni. Untuk menunjang hal ini perlu riset mendalam dan dari hasil risetnya kemudian direkonstruksi kepingan sejarah yang ingin ditinjau.
Di sinilah kelemahan utama film dokumenter sejarah Indonesia. Pernyataan sering tidak didukung oleh data yang kuat. Sering pula terlalu general dan tidak masuk kepada penguatan argumentasi yang tajam dan kokoh, baik data maupun relevansi analisisnya. Padahal, keutamaan sebuah film dokumenter sejarah murni terletak di sini. Film BTDFT terasa sudah berupaya memenuhi unsur ini, tetapi masih jauh dari memadai.
Film sejarah murni berbeda dengan film dokudrama. Dalam film dokudrama dapat disisipi beberapa tafsir yang sesuai dengan kebutuhan dalam komersial. Dibuka peluang imajinasi berdasarkan rekonstruksi sejarah. Sedangkan, untuk film sejarah murni, setiap aspek dan setiap detil harus mendekati fakta yang sebenarnya. Data harus originil dan valid, bukan sekedar argumentasi umum saja.
Film sejarah murni lebih bersandar kepada ilmu pengetahuan yang setiap pernyataan, apalagi penemuan, patut disusun dengan dasar-dasar fakta dan pola pikir yang sistematis.
Kedua, teknis sinematografis yang lihai sehingga membuat gamba-gambar menjadi menarik. Secara umum BTDFT memang telah menghasilkan gambar-gambar yang apik dan menawan. Keindahan Banda terpampang secara apik.
Musik pun sangat menunjang nuansa yang disampaikan kepada penonton. Film BTDFT memang lebih menonjolkan keindahan visual ketimbang menyodorkan aspek sejarahnya sendiri.
(Baca juga: Jay Subyakto klarifikasi soal film Banda)
Sutradara Berbakat
Jay jelas sutradara berbakat. Dia memiliki sense of arts yang tinggi. Dia bakal mampu menghasilkan film cerita panjang yang baik di kemudian hari. Tetapi, memilih film dokumenter panjang sejarah murni sebagai film pertama memang menjadi ujian yang melewati kemampuan seorang sineas awal yang membuat film karya pertama.
Hal ini lantaran selain aspek historis, juga dibutuhkan aspek keilmuan, dalam hal ini ilmu sejarah, sesuatu yang bukan bidang yang digeluti oleh Jay Subiakto. Makanya, niat baik dan keberaniannya perlu kita apresiasi. (*)
*) Wina Armada Sukardi adalah wartawan dan kritikus film.
Oleh Wina Armada Sukardi *)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017