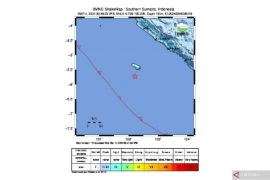Bahasa Enggano itu susah, tulisan dengan lisan itu berbeda. Sulit untuk bisa mencatatkannya."
Enggano, Bengkulu (ANTARA News) - "Yauuwka," kata peneliti LIPI M Fathi Royani dalam bahasa Enggano. Dia tidak menyangka ucapannya menuai protes warga yang mendengar.
"Itu penghinaan namanya. 'Yauuwka' harus diucapkan dengan tegas, tidak boleh ragu-ragu seperti itu," kata Idris Hasibuan, warga Banjarsari, Kecamatan Enggano Bengkulu.
Menurut Idris, "Yauuwka" adalah bahasa asli Enggano yang artinya "selamat lah kita semua". Kata ini harus diucapkan penduduk Enggano saat bertemu satu sama lain.
Fathi Royani dan Idris saat itu hadir dalam kegiatan Participatory Rural Appraisal (PRA) di Desa Banjarsari. Kegiatan itu diselenggarakan tim peneliti etnobotani Pusat Penelitian Biologi LIPI.
Bahasa asli Enggano sangat rumit. Lebih dari lima orang yang ditanya Antara saat mengikuti Ekspedisi Bioresources LIPI di Pulau Enggano mengaku tidak bisa berbahasa asli Enggano.
"Kepala Suku (Meok) bisa. Kalau yang sekarang banyak digunakan itu bahasa Enggano kasar, anak-anak muda mana ada lagi yang bisa bahasa asli Enggano," kata istri mantan Kepala Suku Meok Yominah (73) saat ditemui di rumahnya yang sederhana yang tidak terlalu jauh dari pekuburan Desa Meok.
Saat ditanya apakah ada yang mencatat bahasa Enggano dalam bentuk buku, Yominah kembali menjawab,"Bahasa Enggano itu susah, tulisan dengan lisan itu berbeda. Sulit untuk bisa mencatatkannya".
Kalaupun ada bahasa Enggano sederhana dan masih digunakan hingga saat ini, salah satunya yauuwka. Kata-kata itu biasa diucapkan penduduk pulau terluar Indonesia yang terletak di sebelah barat Bengkulu ini, baik tua maupun muda.
Yominah, yang bisa dikatakan generasi tua di Pulau Enggano, tidak juga bisa melantunkan lagu berbahasa asli Enggano. "Ah, jangan saya (disuruh nyanyi lagu Enggano), saya tidak bisa, salah nanti saya," ujar dia.
Sementara itu, menurut Dara (10), murid kelas V SDN 04 Engano, bahasa Enggano tidak diajarkan di sekolah. Karena itu, jarang ada teman-teman sebayanya yang bisa berbahasa asli Enggano.
Meski tidak mendapat pelajaran khusus bahasa daerah Enggano, namun Dara dengan lancar menyanyikan sebuah lagu Enggano.
Berpegang pada adat
Meski keberadaan bahasa Enggano di ujung tanduk, namun adat dan kebiasaan masyarakat Enggano begitu dipegang kuat.
Saat salah seorang warga Desa Meok, Trisno, yang hendak bernyanyi di atas kendaraan yang sedang bergerak, beberapa ibu-ibu langsung mengingatkannya. Tabu bagi orang Enggano bernyanyi di atas kendaraan saat ada warga lain yang masih dalam masa berkabung. Sanksi adat akan dikenakan kepada yang melanggar.
Kebiasaan atau adat yang juga masih dipegang erat yakni meminta izin kepada enam kepala suku yang memimpin Enggano untuk mengadakan pesta jika hendak menjalankan pernikahan. Pesta adat pernikahan selalu mendahului akad nikah secara Islam bagi suku asli Enggano yang telah memeluk Islam.
Tari Semut juga dipentaskan saat prosesi pernikahan secara adat dilakukan.
"Tari Semut itu yang kemarin malam kita lihat di pesta pernikahan adat. Rombongan mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita dengan berjalan rapat berurutan layaknya rombongan semut yang sedang berjalan," katanya.
Begitu pula Tari Perang, yang menurut Trisno awalnya dipentaskan saat akan terjadi perang, sekarang hanya ditarikan saat menyambut tamu-tamu penting. Tombak-tombak yang sebelumnya digunakan berperang, kini hanya digunakan saat melakukan Tari Perang saja.
Sementara itu, menurut salah seorang warga Desa Meok lainnya, Sri Erliani, tradisi atau adat yang hingga kini masih dipegang oleh masyarakat asli Enggano yakni memakan salai penyu saat pesta pernikahan berlangsung atau saat desa berkabung karena meninggalnya sang kepala suku.
"Salai Penyu pasti ada, itu memang sudah tradisi di Enggano. Kadang memang daging penyu direndang, tapi lebih sering disalai," ujar Sri kepada Antara.
Terkadang jumlah penyu yang dimasak, menurut dia, mencapai 10 ekor. "Penyunya ya kita tangkap. Biasanya di pesisir di Desa Kaana, tempat yang biasa kendaraan lewati saat air laut surut," ujar dia.
Menurut Sri, banyak masyarakat yang sebenarnya tahu jika penyu merupakan hewan dilindungi. Namun demikian sulit membuat masyarakat Enggano berhenti mengkonsumsi daging penyu, karena sudah menjadi adat bagi suku asli Enggano.
Kebiasaan atau tradisi yang juga tidak ditinggalkan di Enggano yakni setiap kepala desa harus memiliki kamiang, sejenis cangkang keong laut berukuran besar yang dijadikan alat pemberitahuan bagi warga desa saat ada musibah, meminta pertolongan, atau memberikan pengumuman, kata mantan Kepala Desa Meok Sunaidi (50).
"Calon kepala desa harus punya kamiang sendiri. Kalau saya dulu cari di laut dangkal, biasanya ada di kedalaman tiga meter, tapi tetap susah mengambilnya," ujar dia.
Kamiang tidak boleh diturunkan ke kepala desa baru. Menurut dia, kepala desa yang baru dikukuhkan harus mencari sendiri cangkang keong raksasa yang dapat menghantarkan bunyi hingga tiga kilometer (km) tersebut.
"Pak Camat pun sudah minta kepada kita (para kepala desa) untuk tetap menggunakan kamiang sebagai tradisi kita," katanya.
Karena itu pula, Sunaidi merasa berat melepas salah satu dari dua kamiang yang dimilikinya setelah peneliti etnobotani LIPI menyampaikan ingin membeli salah satu dari kamiang tersebut untuk ditempatkan di Museum Etnobotani milik LIPI.
Oleh Virna P Setyorini
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015