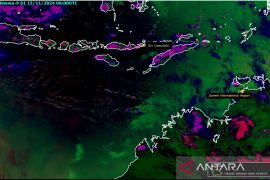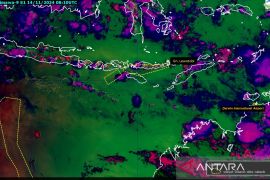memanfaatkan abu vulkanik sebagai pupuk alami, pembenah tanah, dan penangkap karbon jauh lebih murah dibanding usulan lain ...
Jakarta (ANTARA) - Sektor pertanian Indonesia diperkirakan berkontribusi melepas karbon sebagai gas rumah kaca sebanyak 13 persen dari total emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kemudian berkomitmen mengurangi emisi dari sektor lahan, termasuk pertanian, sebesar 58,3 persen pada 2024.
Pemerintah juga mendorong sistem pertanian rendah emisi karbon. Di sisi lain, bidang pertanian menjadi sektor paling rentan terdampak perubahan iklim sehingga ketahanan pangan Indonesia juga terancam.
Indonesia dituntut mempertahankan produksi pertanian sekaligus menekan emisi gas karbon. Berbagai strategi jitu, seperti promosi pertanian organik melalui subsidi pupuk organik dan bantuan pupuk organik, mulai diupayakan Pemerintah.
Tujuannya agar karbon dapat disimpan ke dalam tanah sekaligus memulihkan tanah untuk menopang produksi pertanian. Prinsipnya, pupuk organik harus dikombinasikan dengan pupuk anorganik agar produksi pertanian tidak melandai. Tentu upaya itu layak didukung, diteruskan, dan digaungkan.
Namun, artikel ini membahas upaya lain yang jarang dilirik berbagai pihak, yaitu memanfaatkan abu vulkanik asal semburan gunung berapi.
Abu vulkanik dapat menjadi solusi mempertahankan ketahanan pangan yang berbasis alam. Di negara-negara dengan gunung berapi aktif, seperti Indonesia, abu vulkanik dapat digunakan untuk memasok nutrisi sekaligus mengurangi CO2 dari atmosfer.
Sejujurnya sejak lama pengetahuan abu vulkanik dapat menyuburkan tanah sudah banyak diketahui peneliti, akademisi, bahkan oleh petani klasik.
Namun, manfaat abu vulkanik sebagai pembenah tanah atau pupuk masih terbatas dinikmati oleh para petani di wilayah sekitar gunung berapi di Jawa. Bahkan masih banyak petani yang menikmati kesuburan tanah dari abu vulkanik tanpa sadar bahwa sumber pupuk gratis itu berasal dari semburan gunung berapi.
Sewaktu Gunung Sinabung meletus di Sumatera Utara, para petani mengeluh karena abu gunung berapi merusak tanaman dan mengganggu pertanian. Abu-abu di jalanan dicuci karena mengganggu lalu lintas. Belum ada upaya sistematis memperluas skala memanfaatkan abu vulkanik untuk memperbaiki tanah-tanah miskin hara.
Indonesia memiliki setengah dari jumlah letusan gunung berapi mematikan di dunia. Setiap bulan terjadi letusan gunung berapi yang lebih kecil. Karena letusan yang berulang, tanah di daerah gunung berapi biasanya memiliki lapisan abu yang berlapis-lapis.
Tanah seperti ini dapat ditemukan di dekat 127 gunung berapi aktif dan tidak aktif yang tersebar di pulau-pulau Sumatra, Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, bagian utara Sulawesi, dan Maluku.
Abu sering dianggap sebagai gangguan, tidak banyak digunakan sebagai perbaikan tanah di lahan pertanian, dan belum diteliti dengan memadai sebagai alternatif untuk batu basalt yang dihancurkan.
Di kalangan ilmuwan ilmu tanah, abu vulkanik telah menjadi objek kajian yang menarik sejak dulu kala. Musababnya, selama proses pelapukan abu vulkanik menjadi tanah juga terjadi penyerapan CO2 dari atmosfer yang melimpah.
Ketika disemburkan dari mulut gunung berapi, kandungan karbon organik dari abu vulkanik adalah nol alias nol persen. Namun, ketika berubah menjadi tanah, maka tanah vulkanik dapat memiliki kandungan C-organik sebesar 10 persen. Tanah yang berasal dari abu vulkanik itu disebut andisol atau andosol.
Kata ando berasal dari bahasa Jepang yang bermakna hitam. Tanah yang berasal dari abu vulkanik umumnya berwarna hitam yang menjadi penanda kaya bahan organik. Bandingkan dengan rata-rata kandungan karbon organik pada tanah mineral yang hanya 1 sampai 2 persen.
Warna tanah andosol selain hitam juga merah atau merah kekuningan sebagai penanda tingginya kandungan besi. Selain andosol, tidak ada tanah mineral yang kandungan bahan organiknya di atas 10 persen.
Tanah dengan kandungan bahan organik di atas 10 persen biasanya adalah tanah organik yang juga disebut gambut.
Luasan andisol hanya 1 persen dari luas permukaan bumi, tetapi andisol mengandung sekitar 5 persen dari stok karbon tanah global (Dahlgren et al., 2004).
Abu Vulkanik
Sejumlah peneliti seperti Prof. Dian Fiantis dari Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, mengungkap lapisan tanah permukaan tanah vulkanik di Sumatera Barat mengandung karbon organik rata-rata 4 persen dan dalam beberapa kasus mencapai 15 persen.
Pada tahun 1930-an Mohr, ahli tanah dari Belanda, bahkan mengasosiasikan kepadatan penduduk di tanah Jawa berhubungan erat dengan sebaran tanah andisol. Menurutnya, wilayah terpadat di Pulau Jawa terpusat di area-area tanah subur yang berkembang dari bahan induk abu vulkanik.
Di Indonesia, tanah asal abu vulkanik luasannya menapai 31,7-juta hektar atau 17 persen luas daratannya. Letusan gunung berapi menyediakan abu vulkanik dan tefra.
Namun, tefra tidak banyak digunakan dan belum diinvestigasi dengan memadai sebagai pembenah tanah untuk mengikat karbon. Hitungan penulis yang diterbitkan di Jurnal Soil Security berjudul Applying Volcanic Ash to Croplands–The Untapped Natural Solution mencatat besaran dan peluang potensi pengurangan CO2 dari bahan vulkanik yang diproduksi setiap tahun di Indonesia.
Pada tahun-tahun dengan letusan gunung berapi yang signifikan, pengurangan berikutnya akan mencapai 100-200 juta ton CO2 atau 20-40 persen emisi bahan bakar fosil negara tersebut.
CO2 yang ditangkap ketika bahan vulkanik melapuk merupakan bagian dari siklus karbon global yang jumlahnya tergantung penggunaan lahan.
Ketika abu vulkanik melapuk, pelapukan kimiawi senyawa yang mengandung kalsium dan magnesium menambat CO2 dari atmosfer. Kation dasar yang melapuk dan bikarbonat yang mengendap dalam tanah disimpan sebagai karbon anorganik atau terlarut.
Demikian pula iklim dan vegetasi memengaruhi laju pelapukan termasuk kondisi larutan tanah, pH, dan kondisi redoks. Yang luar biasa, abu vulkanik yang tidak mengandung karbon organik itu secara cepat mampu mengakumulasi karbon.
Musababnya, abu yang telah melapuk merupakan mineral amorf dengan luas permukaan yang besar sehingga memungkinkan memerangkap karbon asal vegetasi yang tumbuh maupun mikroba yang hidup.
Setelah ditangkap, karbon organik bertahan lama dalam tanah karena dilindungi dari aktivitas mikroba oleh kompleks organometalik. Kompleks tersebut membentuk penghalang fisik dan kimia yang mencegahnya dilepaskan kembali ke atmosfer.
Satu eksperimen menunjukkan bahwa abu vulkanik yang baru terendap dapat mengakumulasi karbon organik tanah dengan kecepatan 1,8-2,5 ton CO2 per hektare per tahun melalui pembentukan lumut dan tumbuhan vaskular. Laju ini jauh lebih tinggi daripada sistem manajemen karbon tanah mana pun.
Keistimewaan abu vulkanik itu sering terabaikan karena saat ini abu vulkanik sering tererosi sehingga cepat terbawa air hujan lalu masuk ke sistem akuatik seperti sungai, danau, dan samudera.
Pada konteks ini, peluang abu vulkanik sebagai bahan pembenah tanah, pemberi nutrisi tanah, serta penangkap karbon tanah hilang karena langsung berpindah ke sungai dan laut yang menyebabkan masalah di perairan yang menjadi beban bagi lingkungan. Di perairan, abu vulkanik tidak dapat melapuk dan menangkap karbon secara efektif.
Dengan teknik pengelolaan yang tepat pada lansekap tertentu, memanfaatkan abu vulkanik sebagai pupuk alami, pembenah tanah, dan penangkap karbon jauh lebih murah dibanding usulan lain seperti menambang dan menggiling batuan basal dari luar untuk pupuk dan pembenah tanah.
Abu vulkanik tidak perlu digiling, tetapi dapat menyerap jumlah karbon yang signifikan dari atmosfer, serta memasok nutrisi yang berlimpah bagi kesuburan tanah untuk mewujudkan ketahanan tanah (soil security) dan ketahanan pangan (food security).
Dengan demikian, abu vulkanik dapat dimasukkan dalam akuntansi karbon dan pengelolaannya dapat menjadi bagian dari strategi pengurangan emisi.
Terakhir, jika abu vulkanik tidak digunakan untuk sektor pertanian, maka abu tersebut dapat terbawa oleh sungai atau samudera.
Kemampuan mereka menangkap CO2 masih dapat terjadi di perairan dengan tingkat yang lebih rendah, tetapi menjadi tidak menguntungkan untuk memperbaiki kualitas tanah, mendukung ketahanan pangan, serta tidak berkontribusi menjadi bagian sektor pertanian rendah karbon.
*) Prof. Budiman Minasny, SP, M.Sc,PhD (Profesor Ilmu Tanah dan Lingkungan di University of Sydney, Australia) dan Dr. Destika Cahyana, SP, M.Sc (Peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan, Badan Riset, dan Inovasi Pertanian).
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2023