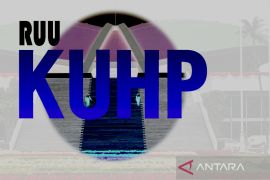penolakan terhadap RKUHP .., semata-mata untuk mempertahankan status quo agar hukum tetap berada dalam ketidakpastiannya.
Jakarta (ANTARA) - Tidak banyak yang tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadikan rujukan aparat pada saat ini merupakan produk hukum yang diterbitkan pada tahun 1.800. Artinya, KUHP yang dipakai oleh jaksa, polisi, hingga hakim di ruang-ruang sidang itu sudah berusia 222 tahun.
KUHP yang digunakan oleh aparat penegak hukum tersebut memiliki orientasi klasik, menekankan kepada kepentingan individu, bukan kepentingan umum atau masyarakat luas apalagi negara.
Pada saat itu, hukum pidana dibuat sebagai sarana lex talionis atau ajang balas dendam kepada orang-orang yang melakukan suatu kesalahan. Sementara, dari perkembangan zaman, prinsip balas dendam tersebut sudah tidak cocok lagi karena ada perubahan paradigma hukum pidana secara universal.
Indonesia yang sudah merdeka 77 tahun hingga kini masih menggunakan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Hal itu tentu saja perlu penyesuaian, salah satunya dengan upaya melahirkan KUHP baru yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.
KUHP yang sudah berusia 2 abad lebih tersebut tentu saja tidak cocok, paling tidak bisa dikatakan sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun dan memperbaharui KUHP yang sesuai dengan situasi dan kondisi era digital dewasa ini.
Pentingnya Indonesia memiliki KUHP baru juga dilatarbelakangi mengenai kepastian hukum. Alasannya, hingga saat ini dari beberapa versi KUHP yang diterjemahkan oleh ahli hukum memiliki pemaknaan yang cukup beragam atau setidaknya mempunyai makna yang berbeda antara satu dengan lainnya.
Jika ditelisik lebih jauh, terjemahan KUHP oleh Moeljatno dan R. Susilo atau Andi Hamzah memiliki makna atau penafsiran yang cukup berbeda. Sementara, hal tersebut telah diajarkan di ruang-ruang belajar kepada mahasiswa atau dijual bebas di berbagai toko buku dan lain sebagainya.
Pertanyaannya, KUHP manakah yang seharusnya menjadi patokan dalam menegakkan keadilan? Hal itu tentu saja menimbulkan polemik tentang kepastian hukum.
Perbedaan tersebut, misalnya, dapat dilihat antara terjemahan Moeljatno dengan R. Susilo. Menurut Moeljatno, Pasal 110 KUHP berbunyi: “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 KUHP dipidana sama dengan perbuatan itu dilakukan”.
Jika merujuk tafsir tersebut maka artinya adalah pidana mati. Sementara, pada pasal yang sama, yakni Pasal 110 terjemahan R. Soesilo, disebutkan bahwa “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 104 hingga 109 KUHP diancam pidana maksimum enam tahun”.
Dari dua terjemahan pasal yang sama tersebut dapat dilihat bahwa pemaknaan hukuman oleh kedua ahli tersebut bagaikan langit dan Bumi. Moeljatno mengartikan sebagai sebuah hukuman mati, sementara R. Soesilo hanya diancam pidana 6 tahun kurungan penjara.
Contoh lainnya ialah Pasal 221 tentang obstruction of justice atau disebut juga sebagai upaya menghalangi/merintangi penyidikan. Moeljatno dan R. Soesilo juga menafsirkan pasal ini secara berbeda.
Oleh Moeljatno, obstruction of justice dimaknai sebagai “menghindari penyidikan”, sementara oleh R. Soesilo berpandangan obstruction of justice diterjemahkan sebagai “melarikan diri”. Sungguh penafsiran yang berbeda sehingga penerapannya di lapangan bisa berbeda, juga mudah memicu perdebatan hukum tak bertepi.
Adanya pemaknaan yang berbeda berbagai versi KUHP tersebut merupakan masalah serius yang harus disikapi secara bijaksana oleh pemangku kepentingan terkait, utamanya DPR dan Pemerintah.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan berbagai penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini masih dibahas, semata-mata untuk mempertahankan status quo agar hukum tetap berada dalam ketidakpastiannya.
Lebih mirisnya, menurut Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, KUHP yang sudah berusia ratusan tahun itu telah dipakai untuk menghukum jutaan orang di Indonesia.
Misi RKUHP
Sejauh ini Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga, tidak terkecuali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), telah menyosialisasikan RKUHP ke berbagai elemen masyarakat. Namun, Kepala Negara menilai hal itu masih kurang cukup terutama soal penjelasan 14 pasal krusial.
14 pasal krusial yang dimaksud ialah living law atau pidana adat yang termuat pada Pasal 2 dan 601, Pasal 67 dan 100 tentang pidana mati, penghinaan presiden (Pasal 218), tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang (Pasal 252).
Berikutnya, penghapusan pasal tentang dokter/dokter gigi yang menjalankan pekerjaan tanpa izin, membiarkan unggas yang merusak kebun/tanah yang telah ditaburi benih Pasal 277.
Tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan (Pasal 280), penghapusan tindak pidana advokat curang, tindak pidana terhadap agama/penodaan agama (Pasal 302), tindak pidana penganiayaan hewan (Pasal 340, ayat 1).
Tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak (Pasal 412), Pasal 429 tentang gelandangan sebagai tindak pidana, Pasal 467 tentang aborsi, tindak pidana perzinaan (Pasal 415), Pasal 416 terkait kohabitasi, dan perkosaan dalam perkawinan (Pasal 477).
Pada 2 Agustus 2022 Presiden Joko Widodo minta jajaran di pemerintahan terus memasifkan sosialisasi RKUHP kepada elemen masyarakat termasuk kalangan mahasiswa. Dari rangkaian sosialisasi RKUHP yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan, terdapat lima misi RKUHP yang akan disampaikan kepada publik.
Pertama, demokratisasi. Artinya, proses penyusunan RKUHP atau dalam RKUHP itu sendiri harus menjamin kebebasan berserikat, berpendapat, berekspresi, maupun kebebasan menuangkan pikiran dan tulisan. Namun, semua kebebasan itu tetap perlu ada pembatasan yang merujuk pada putusan konstitusi.
Misi selanjutnya ialah dekolonisasi. RKUHP yang disusun saat ini akan mengeluarkan atau melepaskan nuansa-nuansa kolonial dalam KUHP yang digunakan oleh aparat penegak hukum saat ini.
Pada dasarnya substansi atau kandungan KUHP di seluruh dunia itu sama. Di Eropa, misalnya, pencurian merupakan tindak pidana sama halnya dengan di Indonesia.
Di Amerika Serikat pemerkosaan merupakan tindak pidana, begitu juga dengan di Indonesia. Namun, dari sekian banyak tindak pidana, hanya ada tiga isu yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Isu itu ialah kejahatan politik, kejahatan kesusilaan, dan terakhir pasal penghinaan.
"Artinya, jika berbicara penghinaan kepala negara atau pejabat publik, penghinaan terhadap pemerintah janganlah dibandingkan antara satu negara dengan yang lain," kata dia.
Misi ketiga dari RKUHP ialah sinkronisasi. Pemerintah bersama DPR berusaha melakukan sinkronisasi terhadap sekitar 200 lebih undang-undang di luar RKUHP. Sinkronisasi tersebut diperlukan dengan tujuan agar tidak terjadi disparitas pidana.
Bila terjadi disparitas pidana maka seseorang yang diadili akan merasa sebagai korban sistem peradilan. Alasannya, terlalu banyak undang-undang di negara ini yang segala sesuatunya terdapat ancaman pidana. Atas dasar itulah perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak terjadi disparitas pidana.
Misi keempat RKUHP ialah konsolidasi. Dalam kebijakan hukum pidana politik, hukum yang diambil pidana adalah rekodefikasi bukan kodefikasi. Dekodefikasi sendiri merujuk pada menarik pasal-pasal tertentu dari KUHP dan dibuatkan undang-undang tersendiri.
Sebagai contoh, kejahatan jabatan yang ditarik dari KUHP dan dibuat undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara, rekodefikasi ialah upaya menghimpun kembali berbagai kejahatan ke dalam suatu rumah besar yang disebut sebagai KUHP.
Kelima, misi dari RKUHP ialah modernisasi. Modernisasi dari hukum pidana perlu dilakukan karena paradigma hukum pidana itu sendiri telah mengalami perubahan karena kehidupan masyarakat juga terus berubah dan berkembang.
Hukum pidana yang awalnya mengutamakan keadilan retributif atau pembalasan, kini berorientasi hukum pidana modern yang merujuk pada tiga keadilan. Ketiganya ialah keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.
Paradigma hukum pidana modern ialah bagaimana menghukum orang yang bersalah agar ia menyadari tindakannya bertentangan dengan hukum, namun pada waktu bersamaan yang bersangkutan juga harus diperbaiki.
Adapun keadilan restoratif ialah milik korban. Para korban tidak hanya dipulihkan tetapi juga direhabilitasi. Orientasi hukum pidana modern terakhir ialah keadilan rehabilitatif yang dimiliki oleh korban maupun pelaku.
Melalui berbagai upaya yang sedang dan telah dilakukan oleh Pemerintah maupun DPR dalam melahirkan KUHP baru, diharapkan panduan hukum pidana yang betul-betul mengedepankan rasa keadilan serta mampu mengakomodasi supremasi hukum di Tanah Air bisa segera terwujud.
Ketika masyarakat terus berubah maka hukum yang mengatur kehidupan sosial juga harus menyesuaikan, tidak terkecuali KUHP. Apalagi bila pasal-pasal yang digunakan itu sudah kelewat uzur, berusia lebih dari 200 tahun.
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2022