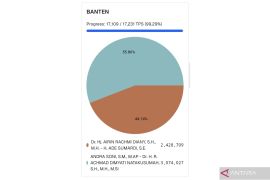Konsentrasi kita dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan di dalamnya, ditenggelamkan oleh mimpi-mimpi yang silih berganti membuai tidur kita. Apa benar kita lebih suka memilih kegelapan agar bebas bermimpi? Kita bangsa besar, tapi di manakah leta
Jakarta (ANTARA News) - Pada 1985, dalam "Dari Pojok Sejarah", Emha Ainun Nadjib yang akrab dipanggil Can Nun, mengandaikan bangsa kita sebagai "ashabul kahfi," tertidur di gua tertutup sepanjang 309 tahun.
Salah seorang penghuni gua, sesudah mereka terbangun, pergi keluar untuk membeli makanan. Ternyata uang yang dibawanya tidak laku lagi di pasar. Mereka, catat Cak Nun, tak bisa tidak, harus menyesuaikan diri dengan segala hukum pasar itu, kecuali mereka bersedia makan batu dalam gua.
Sementara kita, masalahnya jauh lebih rumit dari itu. Kita bahkan tidur lebih lama, 350 tahun! Lalu bangun gelagapan, dan secara sosial, sampai kini belum siuman.
Ada empat kata penting dalam kisah itu; bangun tidur, gua, pasar, dan uang.
Dan kini kita sudah 2010, di era pasar bebas yang tak bisa dielakkan, pelaksanaan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) yang tak bisa ditawar lagi. Tiba-tiba, kita pun bak para pemuda "ashabul kahfi."
Kita harus menyesuaikan dengan pasar dan mata uang yang berlaku, kalau tidak kita terus terkungkung dalam gua. Pertanyaannya, benarkah kita baru bangun tidur? Benarkah kita hidup di gua? Benarkah kita ditinggal oleh pasar dan mata uang?
Meski itu semua pengibaratan, tetapi, saya kira, kita merasa betapa kita belum sepenuhnya siap. Kita belum kokoh sebagai bangsa produsen, padahal zaman kolonial dulu, kita pernah menjadi pengekspor gula terbesar di dunia. Produk tembakau dan hasil bumi kita melimpah. Tetapi, semua itu dalam pengawasan dan manajemen penjajah. Semua hasil untuk penjajah. Bumi dan kekayaan alam kita, dikuras. Ingatkah kita pada zaman tanam paksa dulu?
Kita, dibuat pulas tertidur oleh penguasa kolonial. Zaman normal, kata mereka, adalah zaman ketika segala sesuatu nyaman di bawah kendali mereka. Sebaliknya, yang tidak normal adalah ketika kita berpikir dan bergerak merdeka dari mereka.
Orang-orang yang diasingkan ke Digul dan lainnya, dicap penentang zaman normal. Tapi, para pejuang kemerdekaan Indonesia membalik logika itu. Kita harus merdeka, dan proklamasi, kata Bung Karno, adalah jembatan emas menuju masa depan Indonesia gemilang.
Kemudian, sesudah merdeka, apakah kita benar-benar sudah bangun dari tidur itu? Beberapa tahun lalu, Majalah Newsweek bahkan menyebut Indonesia "the sleeping giant," raksasa yang tertidur. Tubuh kita bongsor dan tampak kuat, tetapi sayang, dibekap tidur pulas.
Syair "bangun tidur, tidur lagi" dari Mbah Surip mungkin benar. Kita memang sudah benar-benar bangun, tapi, mata belum sepenuhnya melek, dan lebih bahayanya, mudah sekali untuk "tidur lagi," "masuk gua" lagi. Dan waktu berjalan cepat, begitu "bangun pagi," kita mendapati diri kita terkejut, lalu "tidur lagi," persis syair lagu Mbah Surip itu.
Para penyair seperti Mbak Surip memang tidak henti membuat kalimat-kalimat membangunkan. Mulai Chairil Anwar dengan "Antara Kerawang dan Bekas," hingga Rendra dalam "Kesaksian" dan Sutardji Calzoum Bachri pada "Tanah Air Mata." Tetapi, itu semua masih sebatas syair, yang menguap begitu selesai dibacakan. Seperti setitik air di Gurun Sahara.
Konsentrasi kita dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan di dalamnya, ditenggelamkan oleh mimpi-mimpi yang silih berganti membuai tidur kita. Benar kata syair epos Mahabaharata bahwa "dalam kegelapan kita bebas bermimpi." Tapi apa benar kita lebih suka memilih kegelapan agar bebas bermimpi? Kita bangsa besar, tapi di manakah letak besar itu?
**
Tahun 1985 juga Cak Nun menulis "Kamar Gelap Sejarah." Bahwa, sejarah itu bagaikan kamar gelap. Kita makin tidak memahami "tingkah laku sejarah," juga pada nilai-nilai yang ditaburkannya.
Kita, mengutip Cak Nun, beramai-ramai diplonco sejarah. Namun, karena kita tak ingin bengong saja, maka dalam kegelapan itu kita mencoba bergerak. Kita saling tubruk, saling protes, saling tuduh, saling menyalahkan. Padahal, kita mempunyai tujuan sama, berjalan ke timur. Seorang dari kita menyebut timur itu di sana, sementara yang lain menunjuknya di sini.
Mungkin kita akhirnya berdamai, tetapi tidak mustahil ada yang masih iseng ingin menabrak, jegal sana jegal sini, lantas terhempas di pojokan.
Persoalannya jelas, kata Cak Nun, kita butuh lampu. Syukur bisa membuat jendela, sehingga matahari benar-benar ada. Kalau tidak ada sama sekali cahaya, kita mungkin harus belajar dari burung hantu.
**
Dan, apakah kita, masih berada di, meminjam istilah Nurcholish Madjid, "terowongan gelap sejarah"? Belumkah kita menemukan setitik cahaya? Bagaimanakah demokrasi berkontribusi?
Faktanya demokrasi kita masih dalam proses menuju titik yang dianggap lebih sempurna. Stasiun demokrasi kita masih, dengan sedih saya harus katakan, meminjam Ahmad Syafii Maarif, "demokrasi perut."
Betulkah masih sebatas urusan perut? Nyuwun sewu, kata orang Jawa, mohon maaf beribu maaf, kelihatannya memang demikian. Orang-orang berebut menjadi politisi, sekedar untuk mencari pekerjaan.
Jelas, kita masih membutuhkab penerangan. Banyak sisi-sisi sejarah kita, seperti diri kita, berada di ruang gelap. Tabrakan sana-sini. Alih-alih bersinergi, yang ada dan terasa, adalah "Ken Arokisme" dalam berpolitik.
Sejarah akan terus berproses, tapi kita harus serius belajar membedakan mana mimpi, mana provokasi memabukkan. Mana visi sejati kita, mana yang gadungan. Mana emas, mana loyang. Mana jalan bengkok, mana yang lurus.
Lampu harus dinyalakan, permainan dan pergumulan sejarah harus terjadi di ruang yang terang. Lebih penting dari itu, kita harus menciptakan jendela. Kita harus melongok keluar, agar bisa membandingkan betapa tertinggalnya kita, akibat "perkelahian" diantara kita di kegelapan itu.
Omong-omong, seperti apakah akhir Pansus Century? Mengubah ruang sejarah kita menjadi semakin terangkah? Atau tetap gelap dan gelap?
*Alfan Alfian, dosen Universitas Nasional, Jakarta
Oleh Alfan Alfian
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010