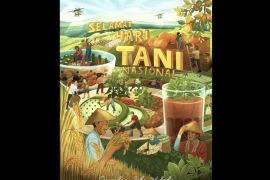Posisi petani di dalam rantai pasok tidak menguntungkan, padahal petani adalah penghasil komoditas. Dengan panjangnya rantai pasok distribusi beras hingga ke konsumen, sudah sepatutnya petani mendapatkan posisi yang lebih baik
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menilai peran petani dalam rantai pasok beras sebagai pemasok utama komoditas tersebut perlu ditingkatkan.
Dalam memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September ini, CIPS menyatakan posisi petani sebagai pihak yang menjual dan memasarkan beras, seharusnya bisa menguntungkan dan lebih memiliki posisi tawar yang menguntungkan.
"Posisi petani di dalam rantai pasok tidak menguntungkan, padahal petani adalah penghasil komoditas. Dengan panjangnya rantai pasok distribusi beras hingga ke konsumen, sudah sepatutnya petani mendapatkan posisi yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan dari harga jual beras di tingkat konsumen," kata Galuh di Jakarta, Kamis.
Pada kenyataannya, rantai pasok beras memang panjang dan seringkali posisi petani tidak menguntungkan karena mereka tidak memiliki kuasa untuk harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG).
Baca juga: Peneliti ingatkan pandemi perparah kondisi pelaku usaha pertanian
Selain itu petani tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan saat bertransaksi karena harga komoditas yang mereka hasilkan sangat bergantung pada pasar. Alhasil, petani hanya bertindak sebagai price taker dan bukan price maker.
Beras lokal dari petani setidaknya melalui empat hingga enam pelaku distribusi sebelum sampai di tangan konsumen. Dalam rantai distribusi beras lokal, margin laba terbesar justru dinikmati para tengkulak, pemilik penggilingan padi, atau pedagang grosir.
Penelitian yang dilakukan oleh Hizkia Respatiadi mencontohkan yang terjadi di Pulau Jawa, margin laba ini berkisar antara 60-80 persen per kilogram. Sebaliknya, margin laba yang didapat pedagang eceran hanya berkisar antara 1,8-9 persen per kilogram.
Meski demikian, rantai distribusi yang panjang ternyata bukan satu-satunya penyebab harga pangan di Indonesia terbilang mahal. Jika dilihat dari ongkos produksi, penelitian yang dilakukan oleh International Rice Research Institute (IRRI) pada tahun 2016 menemukan bahwa ongkos produksi beras di Indonesia 2,5 kali lebih mahal dari Vietnam dan 2 kali lebih mahal dari Thailand.
Baca juga: Lindungi petani sebagai garda terdepan pangan saat pandemi
Studi ini juga menunjukkan rata-rata biaya produksi satu kilogram beras di Indonesia adalah Rp4.079, hampir 2,5 kali lipat biaya produksi di Vietnam (Rp1.679), hampir 2 kali lipat biaya produksi di Thailand (Rp2.291) dan India (Rp2.306). Biaya produksi beras di Indonesia juga lebih mahal 1,5 kali dibandingkan dengan biaya produksi di Filipina (Rp3.224) dan China (Rp 3.661).
Walaupun berperan sebagai tulang punggung sektor pertanian, kesejahteraan petani juga terbilang masih jauh dari yang diharapkan. Dari data BPS di tahun 2018, terdapat total 27,2 juta rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan. Dari jumlah total tersebut, sekitar 15,8 juta tergolong rumah tangga petani gurem atau rumah tangga pertanian dengan lahan kurang dari 0,50 hektare.
"Pandemi COVID-19 menyebabkan hasil panen belum terserap secara maksimal di pasaran. Tidak terserap dengan baiknya komoditas pangan hasil panen ini juga dapat disebabkan karena berkurangnya pendapatan masyarakat ataupun karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Galuh.
Baca juga: Pemerintah akan berikan insentif bagi 2,44 juta petani
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020