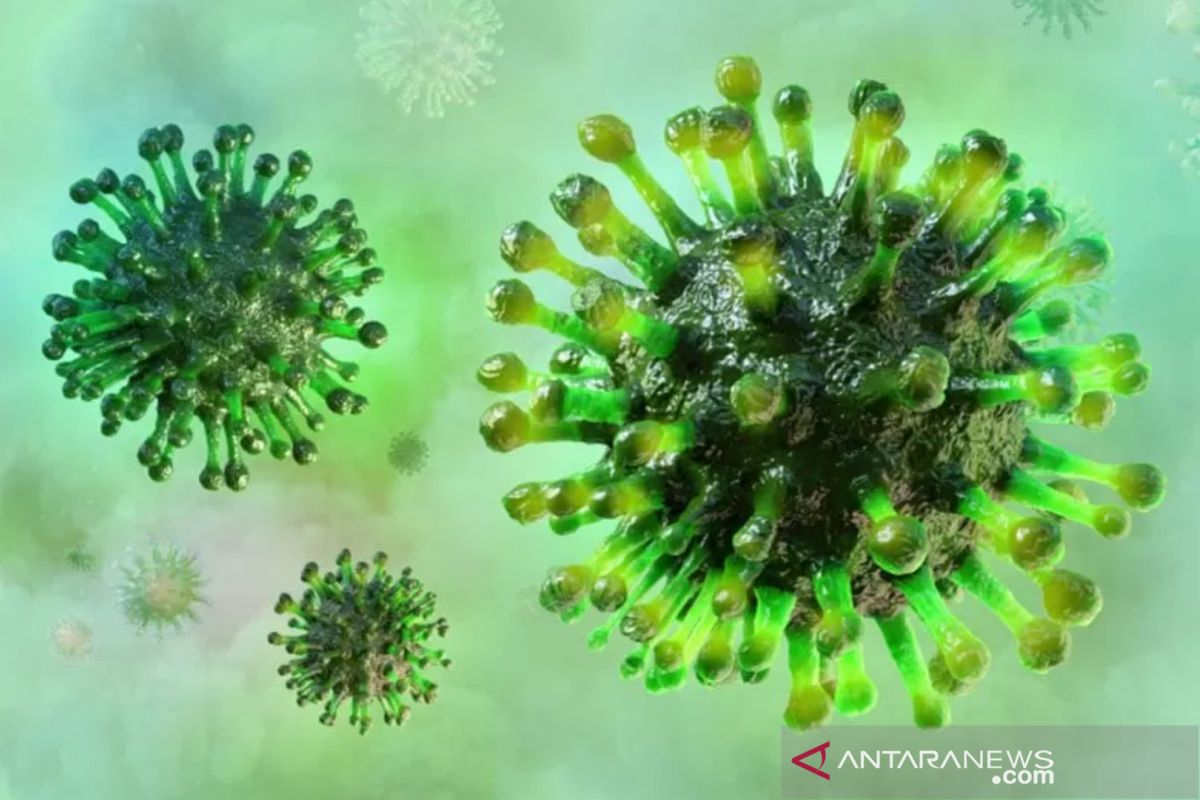Masih butuh banyak penelitian untuk dapat membuka satu per satu tabir yang menyelimuti SARS-CoV-2Jakarta (ANTARA) - Masih banyak pertanyaan belum terpecahkan tentang severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) penyebab coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang hingga 30 April 2020 telah menewaskan 217.769 orang di seluruh dunia.
Penyakit yang disebut-sebut merupakan zoonosis tersebut pertama muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada Desember 2019. Namun masih ada pula negara dan masyarakat dunia yang menyangsikan virus penyebab penyakit COVID-19 tersebut berasal dari kelelawar.
Begitu cepat virus menyebar dan menginfeksi sistem pernafasan, berdampak fatalitas.
Harus diakui, kecepatan infeksi virus membuat banyak negara tergagap oleh krisis kesehatan tersebut. Meski ada pula yang sukses mengendalikannya di level klaster seperti Selandia Baru, Vietnam, Korea Selatan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) awalnya menyebutkan bahwa penularan SARS-CoV-2 melalui tetesan kecil (droplet) dari batuk atau bersin orang yang positif lalu membawa virus tersebut ke tubuh orang lain. Karenanya, hanya mereka yang sakit yang diwajibkan mengenakan masker selain petugas medis dan mereka yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19 tentunya.
Munculnya hasil penelitian yang menemukan virus Corona baru juga diduga menyebar melalui aerosol membuat WHO menganjurkan penggunaan masker untuk masyarakat yang sehat saat beraktivitas di luar rumah sebagai bentuk antisipasi.
Pasalnya, ada orang-orang yang terlihat sehat, tak tampak gejala sama sekali, namun tanpa mereka ketahui ternyata telah memiliki virus tersebut di tubuhnya. Itu yang dikhawatirkan menjadi sumber penularan yang sulit dideteksi.
Baca juga: Indonesia miliki 40 laboratorium bekas penanganan pandemi SARS
“Menumpangi” polutan?
Sebuah hasil analisis awal yang dilaporkan tim peneliti dari setidaknya sembilan universitas dan lembaga penelitian di Italia pada 24 April 2020 lalu yang fokus mencari tahu kaitan antara partikel polutan dan SARS-CoV-2, mendapati virus tersebut ditemukan pada materi partikulat lebih kecil dari 10 mikron (PM10) di Provinsi Bergamo, sebuah wilayah di bagian utara Italia yang juga diketahui sebagai pusat industri.
Tingkat infeksi SARS-CoV-2 di daerah-daerah yang berada di Lombardy dan Lembah Po yang merupakan wilayah di bagian utara Italia memang tercatat tinggi. Daerah-daerah tersebut juga diketahui memiliki polutan dengan konsentrasi tinggi yang juga diketahui memiliki efek negatif pada kesehatan manusia.
Italia mencatat 30 persen pasien positif COVID-19 di negara tersebut hidup di Lombardy, sedangkan 13,5 persen pasien yang terinfeksi virus yang sama hidup di Emilia Romagna, 10,5 persen ada di Piedmont dan 10 persen lainnya ada di Veneto.
Sebelumnya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health mengonfirmasi hubungan antara peningkatan konsentrasi PM dan tingkat kematian karena COVID-19.
Kondisi itu yang juga melatari Leonardo Setti dan rekan-rekannya melakukan penelitian tersebut dan menghasilkan analisis awal berjudul SARS-Cov-2 RNA Found on Particulate Matter of Bergamo in Northern Italy: First Preliminary Evidence yang dimuat di medRxiv.
Hasil analisis awal mereka didapat dari meneliti 34 sampel PM10 luar ruang atau udara dari lokasi industri Provinsi Bergamo yang dikumpulkan dengan dua sampel udara berbeda selama periode tiga minggu secara terus menerus, dari 21 Februari sampai dengan 13 Maret 2020.
Sampel-sampel tersebut dites dan telah menunjukkan secara wajar keberadaan ribonucleic acid (RNA) virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi gen RtDR yang sangat spesifik pada delapan filter dalam dua analisis Polymerase Chain Reaction (PCR) paralel.
Sekali lagi hasil penelitian tersebut hanya analisis awal, sehingga tidak boleh digunakan untuk memandu praktik klinis. Setti dan rekan-rekannya juga menegaskan masih perlu ada konfirmasi lebih lanjut dari bukti awal itu dan saat ini sedang berlangsung, dan harus mencakup penilaian real-time tentang vitalitas SARS-CoV-2 serta virulensi ketika teradsorpsi pada partikel.
Saat ini, tidak ada asumsi yang dapat dibuat mengenai korelasi antara keberadaan virus pada PM dan pengembangan wabah COVID-19.
Baca juga: COVID-19 bisa berhenti menyebar saat musim kemarau?
Penelitian tambahan
Hal senada juga disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia (Gubes UI) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prof Dr Budi Haryanto, bahwa penelitian awal itu masih harus ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian lain untuk mengonfirmasi kebenaran hasil penelitian awal, harus konklusif.
WHO yang, menurut dia, memiliki wewenang menetapkan apakah penularan virus tersebut ada di udara (airborne) atau tidak.
Prof Budi mengatakan ketika SARS-CoV-2 benar ada di PM10 artinya virus tersebut ada di udara. Itu akan menjadi lebih mengerikan karena bisa terbang ke mana-mana.
Karenanya ia menegaskan harus ada penelitian tambahan, karena jika benar virus dapat melekat pada PM10 atau udara maka itu mematahkan pemahaman sebelumnya bahwa cara hidup SARS-CoV-2 yang selama ini diketahui “rumahnya” di cairan, dalam hal ini tetesan kecil (droplet).
“HIV sama, harus ada medianya. Tapi ketika darah itu kering dia akan mati. Harus ada ‘kendaraannya’. Sampai sekarang COVID-19 ini masih dengan ‘kendaraan’ droplet. Jadi harus menunggu (hasil penelitian lain), kalau konklusif maka WHO akan sebutkan itu ‘airborne’,” ujar Prof Budi.
Kasubdit Informasi Pencemaran Udara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Suradi pun mengatakan penelitian tersebut masih harus dikembangkan.
Ukuran virus penyebab COVID-19 sekitar 0,12 mikron. Namun, ia mengatakan perlu dipahami kalau seandainya benar SARS-CoV-2 ternyata airborne maka tidak mungkin virus tersebut “telanjang”. Artinya, kalau melayang-melayang di udara maka virus tersebut akan terselubungi oleh fluida sehingga ukurannya akan bergantung dari seberapa lama masa hidupnya di udara.
SARS-CoV-2, diakui para ilmuwan dan akademisi memiliki karakter unik dan sering kali tak terduga. Masih butuh banyak penelitian untuk dapat membuka satu per satu tabir yang menyelimutinya.
Baca juga: Penyebaran COVID-19 ternyata lebih mirip Flu daripada SARS
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2020